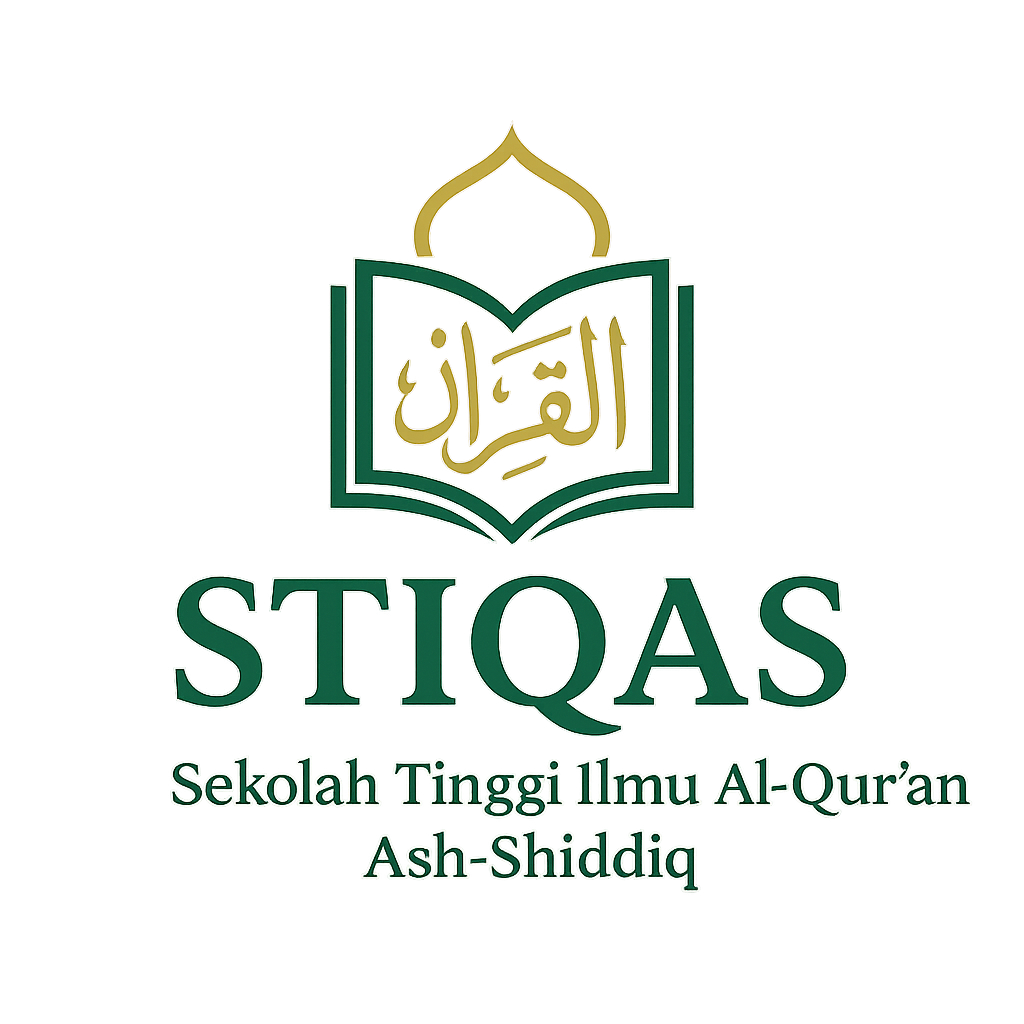Setiap tahun, ribuan mahasiswa berdiri rapi mengenakan toga, menunggu giliran namanya dipanggil. Senyum terukir, kamera menyala, dan tepuk tangan bergema di aula wisuda. Pada momen itu, satu fase hidup dinyatakan selesai: masa kuliah. Namun, di balik euforia tersebut, terselip sebuah transisi yang sering kali tidak dibicarakan secara jujur—peralihan dari mahasiswa menjadi lulusan yang benar-benar siap kerja.
Sebagai pengamat yang kerap berada di sekitar lingkungan kampus, ruang diskusi alumni, hingga forum pencari kerja, satu pola yang terus berulang terlihat jelas: gelar sarjana tidak otomatis berbanding lurus dengan kesiapan menghadapi dunia profesional. Banyak lulusan yang cemerlang secara akademik justru tampak gamang ketika berhadapan dengan realitas kerja yang menuntut kecepatan, ketahanan mental, dan kemampuan adaptasi tinggi.
Di dalam kampus, mahasiswa hidup dalam struktur yang relatif jelas. Jadwal ditentukan, silabus tersedia, dan indikator keberhasilan dirumuskan dalam angka—IPK, nilai, atau kelulusan mata kuliah. Dunia kerja, sebaliknya, jarang menyediakan peta yang serapi itu. Target bisa berubah sewaktu-waktu, evaluasi bersifat subjektif, dan keberhasilan sering kali ditentukan oleh faktor non-akademik seperti komunikasi, inisiatif, dan kemampuan bekerja sama.
Observasi terhadap mahasiswa tingkat akhir menunjukkan adanya jurang ekspektasi yang cukup dalam. Banyak yang masih memandang dunia kerja sebagai kelanjutan linear dari perkuliahan: datang, mengerjakan tugas, lalu pulang. Kenyataannya, pekerjaan menuntut keterlibatan emosional dan intelektual yang lebih kompleks. Di sinilah transisi mulai terasa berat—bukan karena kurang pintar, tetapi karena kurang siap secara mental dan praktis.
Salah satu fenomena yang paling sering terlihat adalah kebingungan identitas. Selama bertahun-tahun, identitas “mahasiswa” melekat kuat: aktif organisasi, mengerjakan tugas kelompok, atau sekadar nongkrong di kantin kampus. Ketika status itu hilang, sebagian lulusan merasa kehilangan pijakan. Mereka tidak lagi memiliki kalender akademik sebagai penanda waktu, tidak ada dosen sebagai otoritas utama, dan tidak ada batasan jelas antara “belajar” dan “bekerja”.
Di ruang tunggu wawancara kerja, misalnya, terlihat lulusan baru yang membawa CV dengan daftar panjang pengalaman organisasi, tetapi kesulitan menjelaskan kontribusi nyatanya. Ini bukan kesalahan personal semata, melainkan refleksi dari sistem pendidikan yang sering menekankan partisipasi dibandingkan refleksi. Mahasiswa diajak aktif, tetapi jarang diajak menerjemahkan aktivitas tersebut ke dalam konteks profesional.
Kesiapan kerja juga kerap disalahartikan sebagai penguasaan hard skill semata. Banyak lulusan fokus mengejar sertifikat, kursus daring, atau kemampuan teknis tertentu. Upaya ini tentu penting, tetapi observasi di lapangan menunjukkan bahwa soft skill justru menjadi penentu utama dalam tahun-tahun awal kerja. Kemampuan menerima kritik, mengelola konflik, dan bertahan dalam tekanan sering kali lebih krusial dibandingkan kemampuan teknis yang bisa dipelajari sambil jalan.
Menariknya, lulusan yang pernah bekerja paruh waktu atau magang cenderung lebih cepat beradaptasi. Bukan karena mereka lebih pintar, tetapi karena mereka sudah terbiasa dengan ritme kerja, hierarki organisasi, dan ekspektasi profesional. Pengalaman ini memberi gambaran realistis bahwa dunia kerja tidak selalu ideal, dan justru di situlah pembelajaran sesungguhnya terjadi.
Di sisi lain, kampus sering kali berada dalam posisi dilematis. Di satu pihak, ia dituntut menjaga idealisme akademik. Di pihak lain, ia diharapkan menghasilkan lulusan siap pakai. Observasi terhadap kurikulum menunjukkan bahwa upaya menjembatani dua tuntutan ini masih setengah hati. Mata kuliah kewirausahaan atau pengembangan karier ada, tetapi sering diperlakukan sebagai pelengkap, bukan kebutuhan utama.
Akibatnya, tanggung jawab transisi banyak dibebankan pada individu mahasiswa. Mereka yang proaktif akan mencari peluang magang, membangun jejaring, dan mengasah diri di luar kelas. Sementara itu, mereka yang mengikuti alur formal kampus saja berisiko tertinggal. Dunia kerja, sayangnya, tidak memberi waktu bagi proses “mengejar ketertinggalan” yang terlalu lama.
Fenomena lain yang patut dicermati adalah tekanan sosial pasca-wisuda. Pertanyaan sederhana seperti “sudah kerja di mana?” atau “kapan mulai kerja?” dapat menjadi beban psikologis tersendiri. Banyak lulusan merasa gagal bukan karena belum bekerja, tetapi karena membandingkan diri dengan standar kesuksesan yang dibentuk media sosial dan lingkungan sekitar. Padahal, transisi setiap orang berjalan dengan ritme berbeda.
Dalam konteks ini, kesiapan kerja seharusnya dipahami sebagai proses, bukan status. Seseorang tidak serta-merta “siap” pada hari kelulusannya. Kesiapan dibangun melalui pengalaman, refleksi, dan kegagalan kecil yang berulang. Observasi terhadap lulusan yang bertahan dan berkembang menunjukkan satu kesamaan: mereka mau belajar ulang, bersedia mengakui keterbatasan, dan tidak menganggap gelar sebagai titik akhir.
Dunia kerja juga perlu dilihat sebagai ruang pembelajaran lanjutan. Jika kampus adalah laboratorium teori, maka tempat kerja adalah laboratorium praktik yang jauh lebih dinamis. Lulusan yang mampu memosisikan diri sebagai pembelajar, bukan sekadar pencari gaji, cenderung lebih tahan terhadap perubahan dan tekanan.
Pada akhirnya, transisi dari mahasiswa menjadi lulusan siap kerja bukan soal seberapa cepat mendapatkan pekerjaan pertama, melainkan seberapa siap seseorang menjalani proses pendewasaan profesional. Ini adalah fase di mana idealisme diuji, ekspektasi diluruskan, dan identitas baru dibentuk—bukan lagi sebagai mahasiswa, tetapi sebagai individu yang bertanggung jawab atas perannya di masyarakat.
Wisuda memang menandai akhir masa kuliah, tetapi kesiapan kerja lahir dari kesadaran bahwa belajar tidak pernah benar-benar selesai. Di sanalah transisi sejati berlangsung: ketika toga disimpan, realitas dimulai, dan seseorang belajar berdiri tanpa silabus yang pasti.